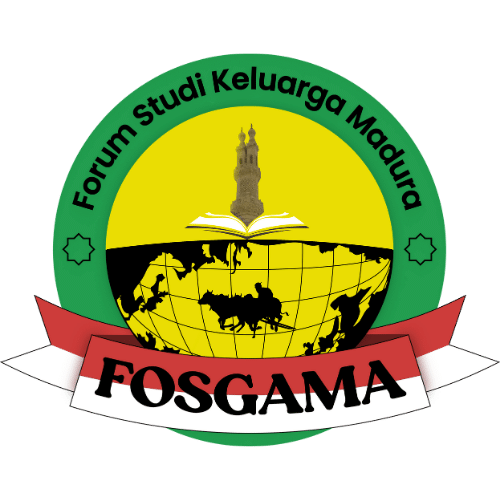FOSGAMA Mesir – Pembaharuan pemikiran Islam merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Realitas dan kondisi sosial masyarakat pada setiap masa pasti berubah, sehingga memerlukan sikap dan pandangan yang berbeda pula.
Perspektif lama yang mungkin sesuai pada era tertentu, irrelevan untuk digunakan di lain waktu karena tidak lagi sejalan dengan perubahan konteks yang terjadi.
Sedangkan Islam sedari awal sudah menegaskan statusnya sebagai agama yang abadi dan akan tetap eksis selamanya, dalam arti sesuai pada setiap masa.
Maka eksistensi dan relevansi ajaran Islam bergantung pada keterbukaan terhadap pemikiran-pemikiran baru sesuai kondisi yang mengitari.
Disiplin keilmuan Islam yang bisa dijadikan sebagai objek kajian upaya pembaharuan pemikiran beragam, ada yang bersifat metodologis seperti ushul fikih, ulumul quran dan musthalah hadis, di samping yang berupa produk dari ilmu-ilmu metodologis tersebut seperti fikih dan tafsir.
Khusus model pertama, karena berposisi sebagai alat untuk memproduksi pemahaman terhadap dua sumber ajaran Islam Alquran dan Hadis, tidak heran jika disiplin ilmu yang bercorak demikian seringkali dijadikan sasaran tembak dalam diskusi tentang pembaharuan.
Pada saat yang bersamaan, aspek legalitas syariah memiliki porsi besar dalam ajaran Islam. Sebab keseharian umat muslim dalam hal relasi vertikal dengan tuhan, maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia tidak bisa dilepaskan dari tinjauan halal-haram perspektif syariah.
Keadaan ini membuat bangunan keilmuan yang berkaitan dengan sisi hukum legal Islam kemudian lebih dominan dibahas dibanding bidang keilmuan lainnya.
Bangunan keilmuan yang dimaksud yaitu ushul fikih sebagai metodologi untuk menghasilkan hukum dan fikih sebagai konklusi hukum hasil dari analisis ushul fikih.
Tetapi perbincangan mengenai pembaharuan pemikiran Islam kerap menjadikan ushul fikih sebagai objek kajian utama, karena fungsi vitalnya sebagai metode untuk menghasilkan fikih.
Ketika metode ini sudah diperbaharui secara otomatis produk yang berupa hukum fikih juga akan ikut terbaharui.
Jika dipetakan, tawaran pembaharuan metodologis bangunan keilmuan hukum Islam secara umum terbagi menjadi dua kecenderungan:
Pertama, pembaharuan bagian-bagian tertentu di dalam ilmu ushul fikih, dengan tetap mempertahankan beberapa metode yang dianggap masih relevan dan masih dalam bungkusan ilmu ushul fikih klasik.
Kedua, pengajuan metodologi alternatif yang terlepas dari ciri khas ushul fikih yang kental akan unsur dialektika linguistik bahasa arab.
Termasuk di antara penganjur pembaharuan model kedua ialah Muhammad Thahir bin Asyur, seorang ulama progresif dari Tunisia.
Dia berpandangan bahwa pembaharuan ushul fikih tidak bisa dilakukan di beberapa bagian saja, karena problem yang terdapat di dalam ilmu ini fundamental.
Masalah yang dimaksud oleh Thahir bin Asyur adalah disfungsi dan disorientasi ushul fikih. Mayoritas topik pembahasan di ushul fikih berkutat pada perdebatan kebahasaan yang problematik, sehingga tidak bisa dijadikan standar utama untuk mengukur kebenaran pendapat layaknya sebuah ilmu metodologis.
Muatan kebahasaan yang begitu besar juga membuat tema-tema lain yang tidak kalah penting, seperti mashalih mursalah dan munasabah menjadi terlupakan.
Padahal pembahasan akan tema-tema ini penting untuk mengetahui maksud dan tujuan awal syariat. Hingga pada akhirnya dia menawarkan alternatif metodologi baru yang dia sebut dengan ilmu maqashid as-syariah.
Sebagai sebuah tawaran baru, elaborasi lebih jauh terhadap konsep maqashid as-syariah Ibn Asyur perlu dilakukan, untuk melihat sejauh mana metodologi alternatif ini bisa menjadi solusi pembaharuan ilmu ushul fikih.
Adapun cara yang akan ditempuh dalam tulisan kali ini ada dua tahapan: Pertama, pembacaan refrensi primer secara langsung. Kitab karya Thahir bin Asyur yang akan dijadikan sebagai refrensi primer adalah maqashid as-syariah al-islamiyah. Analisis refrensi primer ini penting dilakukan guna memahami konsep yang ditawarkan langsung dari penggagasnya.
Kedua, pembacaan rujukan sekunder. Dalam menelaah tawaran maqashid as-syariah Ibn Asyur, rujukan sekunder yang akan dijadikan pembanding yaitu kitab masyahid min al- maqashid buah karya Abdullah bin Bayyah.
Kedudukan Ibn Bayyah sebagai salah satu ulama kontemporer kenamaan yang konsentrasi pada kajian terkait maqashid syariah menjadi alasan utama.
Hasil pembacaan terhadap dua refrensi primer dan sekunder di atas, akan disajikan dalam posisi vis a vis antara problem ilmu ushul fikih yang dikritik Ibn Asyur dengan alternatif yang dia ditawarkan.
Penyajian seperti ini mempunyai keunggulan dalam menyibak kelemahan dan keunggulan masing-masing, dibanding penjelasan satu konsep tanpa adanya singgungan pada konsep yang menjadi antitesis.
Biografi dan Keistimewaan Pembaharuan Thahir bin Asyur
Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Thahir bin Asyur lahir pada tahun 1879 M. atau 1296 H. di daerah Al-Marsa pinggiran ibu kota Tunisia.
Sejak kecil, Thahir bin Asyur hidup di tengah-tengah keluarga terhormat yang lekat dengan nuansa keilmuan. Jenjang pendidikan pertama dia adalah menghafal Alquran di bawah bimbingan Syaikh Muhammad Al-Khayyari di masjid Sidi Abi Hadid.
Setelah itu dilanjut dengan menghafal kitab matan dasar, seperti Ajurumiyah dalam bidang gramatika arab, dan Ibn Asyir dalam ilmu fikih Madzhab Maliki.
Pada tingkatan selanjutnya, Thahir bin Asyur melanjutkan studi ke masjid Zaituna pada tahun 1893 M. Di masjid Zaituna, dia belajar ulumul quran, qira‟at, hadis, fikih dan ushul fikih Maliki, mantiq dan disiplin ilmu lainnya.
Selain ilmu-ilmu keagamaan tersebut, di bawah bimbingan Ahmad bin Wannas Al-Mahmudi, Thahir bin Asyur juga belajar bahasa Prancis. Hingga pada tahun 1899 M. dia mendapatkan ijazah tahtwi’ sebagai tanda lulus dari jenjang pendidikan tsanawiyah di masjid Zaituna.
Thahir bin Asyur juga memiliki beberapa jabatan penting berkaitan dengan strata keagamaan di Tunisia. Tanggung jawab yang pernah diemban oleh Ibn Asyur adalah sebagai: Qadi Madzhab Maliki pada tahun 1913 M., Syaikh Islam Maliki tahun 1932 M., Syaikh masjid Zaituna pada 1944 M. dan terakhir sebagai rektor Universitas Zaituna di tahun 1956 M.
Jabatan- jabatan ini membuat pengaruh dia dalam segi intelektual keislaman di Tunisia secara khusus begitu besar. Thahir bin Asyur wafat pada hari Ahad, 12 Agustus 1973 M. dimakamkan di komplek kuburan Zallaj.
Pemikiran Thahir bin Asyur—khususnya tentang maqashid syariah—menarik untuk dikaji, karena kritik terhadap ushul fikih yang dia lancarkan disertai dengan tawaran konsep yang komprehensif dan cukup rapi.
Berbeda dengan beberapa pemikir muslim yang juga gencar melancarkan kritik terhadap ilmu ushul fikih, namun tidak mampu mendatangkan konsep baru sebagai alternatif. Ada juga yang berupaya menawarkan tatanan baru, tetapi masih berada di bawah bayang-bayang corak ushul fikih lama.
Pemaparan Thahir bin Asyur tidak hanya berhenti dalam tataran konsep saja. Dia juga memberikan contoh aplikasi dari setiap kaidah baru yang diajukan, sehingga tawaran maqashid syariah matang secara konsep dan implementasi layaknya formasi keilmuan klasik.
Lain halnya sebagian pemikir yang hampir sukses mengajukan tawaran kaidah baru yang lepas dari kecenderungan ulama terdahulu, namun kesulitan ketika masuk dalam aspek implementasi.
Usaha Thahir bin Asyur untuk merapikan tawaran konsep baru pengganti ushul fikih dan menyusunnya dalam satu kitab khusus, menjadikan dia sebagai orang ketiga setelah Ibn Abdis Salam dan As-Syathibi yang secara khusus membahas maqashid syariah dalam satu kitab.
Uniknya lagi, dia tidak hanya dalam posisi penyempurna dari apa yang sudah digagas oleh dua ulama sebelumnya, justru dalam beberapa tempat dia berani berbeda pandangan dengan mereka.
Muara Problem Ushul Fikih
Ideal dari sebuah ilmu metodologis adalah menjadi penengah dari perbedaan yang terjadi pada produk hasil metodologi tersebut.
Semisal dalam pembahasan ilmu Akidah yang berpatokan pada kaidah-kaidah ilmu mantik sebagai metodologi berpikir.
Perbedaan yang terjadi di antara para ulama akidah dicarikan pemecahnya di ilmu mantik. Pendapat yang benar adalah yang sesuai dengan kaidah mantik dan pendapat yang sebaliknya dipastikan salah.
Ini terjadi karena kaidah-kaidah dalam ilmu mantik merupakan kaidah yang sudah disepakati, hampir tidak ada perbedaan di antara para ahli mantik kecuali dalam hal-hal parsial yang tidak mempunyai dampak signifikan.
Hal yang berbeda terjadi di ilmu ushul fikih, situasi ideal yang demikian tidak bisa diwujudkan. Ilmu yang pertama kali dikodifikasikan oleh Imam Syafi‟i ini tidak bisa menjadi penengah dari perbedaan yang terjadi di ilmu fikih.
Karena kaidah-kaidah yang terdapat di ilmu ushul fikih sendiri masih diperdebatkan, sehingga perdebatan yang pada awalnya berada di ranah fikih masih harus diperpanjang lagi pada ranah ushul fikih.
Padahal salah satu tujuan dan manfaat dari pembelajaran ushul fikih adalah supaya menjadi standar dalam proses komparasi pendapat yang berbeda di antara para ulama fikih, sehingga bisa dipilah mana pendapat yang kuat dan yang lemah.
Ketidakmampuan ushul fikih untuk menjadi penengah disebabkan oleh asal pengambilan kaidah. Secara umum, asas kaidah ushul fikih ada 4:
Pertama, Alquran dan Hadis. Dua sumber utama semua bangunan keilmuan Islam ini memiliki andil besar dalam melahirkan sebagian besar kaidah-kaidah ushul fikih, seperti penetapan dalil-dalil hukum, cara memecahkan kontradiksi yang ada pada teks-teks dalil, dan urutan skala prioritas dari setiap dalil.
Kedua, Ilmu kalam yang berperan untuk menetapkan kehujjahan Alquran dan Hadis, serta mengetahui status kedudukan Rasulullah Saw. guna memahami perbuatan dan perkataan beliau yang bisa dijadikan hujjah hukum dan tidak.
Ketiga, Bahasa arab. Penggunaan bahasa arab sebagai bahasa Alquran dan Hadis meniscayakan pengetahuan terhadap ketentuan kebahasaan, supaya perintah dan larangan yang terkandung di dalam dua sumber hukum tersebut bisa dipahami dengan baik.
Asal pengambilan kaidah ketiga ini juga mempunyai muatan yang cukup besar dalam pembahasan ilmu ushul fikih. Indikasi amr, nahi, muthlaq, muqayyad semuanya disarikan dari aturan-aturan bahasa arab.
Keempat, Ilmu fikih. Kaidah metodologis ushul fikih memerlukan peran fikih untuk membuktikan bahwa kaidah tersebut tidak hanya berputar di taraf konsep, tetapi juga teraplikasikan dalam ranah hukum. Dalam bahasa lain, ilmu fikih dibutuhkan untuk melegitimasi kebenaran kaidah ushul fikih secara praktis.
Asas pertama dan kedua tidak ada problem sama sekali. Alquran dan Hadis mutlak dibutuhkan dan ilmu kalam berperan sebagai pembenar serta penguat.
Keberadaan fikih sebagai asas keempat juga tidak menjadi masalah, karena hanya pelengkap legitimasi kaidah bukan asas awal seperti tiga lainnya.
Problem utama ada di asas bahasa arab, karena ketentuan kebahasaan sendiri masih diperdebatkan, yang berefek domino pada kaidah ushul fikih yang diambil dari ketentuan problematik tersebut.
Muncul kemudian perdebatan-perdebatan seputar kaidah ushul fikih yang bersumber dari ketentuan kebahasaan, misal apakah indikasi amr pada wajib atau tidak, lafal umum sebelum dikhususkan qathiy atau dzanni dan lain sebagainya.
Masalah asas bahasa arab ini tidak hanya terdapat pada ketentuan problematik di atas, tetapi juga di muatannya yang begitu besar sehingga mengalihkan fokus pengkaji dalil hukum Islam dari maksud utama di balik penetapan hukum.
Mereka lebih berkonsentrasi untuk menelaah sisi tersurat dari teks dengan berpatokan pada aturan kebahasaan, dibanding menyingkap maksud tersirat yang berada di belakang nas dalil hukum.
Salah satu contoh kasus hukum yang menggambarkan secara jelas dominasi aspek bahasa adalah hukum babi laut.
Sebagian ulama seperti Abu Hanifah dan Laist bin Sa‟ad berpendapat kalau babi laut haram dimakan, karena sama-sama mempunyai nama babi sebagaimana hewan yang hidup di darat, meskipun keduanya tidak memiliki kemiripan dalam segi bentuk fisik.
Nas Alquran surah Al-Maidah ayat 3 secara jelas mengharamkan umat muslim mengkonsumsi babi, maka hewan yang mempunyai kesamaan nama juga diharamkan berlandaskan ayat tersebut.
Pendapat ini muncul karena fokus berlebihan terhadap sisi kebahasaan, maksud dari penetapan keharaman babi pun menjadi teralihkan.
Padahal tujuan dari pengharaman konsumsi babi adalah agar terhindar dari efek negatif yang akan ditimbulkan akibat mengkonsumsi hewan itu, bukan sekedar karena faktor penamaannya dengan sebutan babi.
Disfungsi ilmu ushul fikih, dari kedudukan idealnya sebagai standar penyelesai perbedaan pendapat terkait hukum sesuatu menjadi ilmu yang memiliki persoalan tersendiri, juga disorientasi yang bisa ditemukan pada kasus terakhir di atas, menjadi dua alasan pokok kritik Thahir bin Asyur.
Sebagai solusi, dia lalu menawarkan metode lain untuk memahami perintah dan larangan yang terdapat di Alquran dan Hadis, sebagaimana akan dibahas pada sub bab setelah ini.
Konsep Ilmu Maqashid As-Syariah
Tawaran konsep Thahir bin Asyur dalam menyelesaikan sisi problematik kebahasaan ilmu ushul fikih bisa dipetakan menjadi dua bagian:
Pertama, pengambilan kaidah dari prinsip- prinsip yang qothiy atau setidaknya dihasilkan dari penalaran kuat yang hampir tidak menimbulkan perdebatan di dalamnya.
Bagian pertama ini tergambarkan dalam metodologi penetapan maqashid as-syariah. Thahir bin Asyur menyerap kaidah-kaidah mantik yang qothiy atau dekat dengan kapasitas qothiy, dengan tanpa menafikan kaidah ushul fikih yang juga memiliki kapasitas serupa dan mengemasnya dalam balutan ilmu maqashid as-syariah.
Pola pengambilan ini menunjukkan bahwa dia tidak menegasikan ilmu ushul fikih secara keseluruhan, yang dikritik hanya dominasi nalar lughawi yang berlebihan.
Kaidah yang disarikan dari prinsip tersebut menghasilkan beberapa maqashid as-syariah yang juga tidak perlu diperdebatkan dan yang paling penting adalah fitrah, sehingga Thahir bin Asyur kemudian menjadikannya sebagai patokan utama dalam proses penetapan hukum.
Kedua, keengganan untuk memanfaatkan dilalah kebahasaan memunculkan masalah tersendiri ketika dihadapkan pada Alquran dan Hadis yang berbahasa arab.
Pada kasus Hadis secara khusus, Thahir bin Asyur lalu mengajukan metode pembagian Hadis berdasarkan posisi Rasulullah Saw. ketika bersabda beserta konteks yang mengelilingi.
Langkah serupa sudah pernah ditempuh oleh Al-Qarafi dan Ibn Asyur datang menyempurnakan serta melengkapinya.
Tetapi sebelum jauh membahas tatanan metodologi maqashid as-syariah, penjelasan secara definitif perlu terlebih dahulu dilakukan, karena status benar-salah dari setiap konsep tidak bisa diketahui kecuali sudah dipahami secara baik apa yang dimaksud konsep tersebut.
Definisi Maqashid As-Syariah
Thahir bin Asyur mendefinisikan maqashid as-syariah sebagai:
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث التختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة
Artinya: makna dan hikmah yang dituju oleh syari’ di semua atau sebagian besar proses pensyariatan, sekiranya makna dan hikmah tersebut tidak hanya dimaksudkan pada sebagian hukum secara khusus.10
Definisi ini bukan definisi yang rapi secara logika, karena tidak tersusun dari jins dan fasl seperti dalam ketentuan ilmu mantik. Tetapi bukan saja versi Ibn Asyur, dalam catatan Abdullah bin Bayyah bentuk yang serupa juga ada pada definisi-definisi maqashid as-syariah menurut ulama sebelum Thahir bin Asyur .
Ibn Bayyah juga melontarkan kritik pada definisi ini. Dia berpendapat, jika maqashid as-syariah dipahami demikian maka metode ini akan kesulitan ketika digunakan untuk memahami teks-teks dalil hukum, karena menafikan indikasi-indikasi yang hanya bisa dipahami secara bahasa.
Semisal jika dihadapkan pada makna قروء di ayat 228 surah Al- Baqarah, maqashid as-syariah tidak bisa menjelaskan makna dari lafal tersebut, karena bentuknya mujmal dan satu-satunya cara adalah dengan merujuk pada pola pemaknaan secara bahasa.
Namun tanggapan Ibn Bayyah ini tidak akurat secara konteks, karena sedari awal Ibn Asyur memang berupaya lepas dari nuansa kebahasaan yang menjadi ciri ushul fikih, sehingga definisi dia sudah mencerminkan maksud yang dituju.
Tidak saja dalam definisi, dia juga berupaya keras menjaga jarak dengan penggunaan aturan-aturan bahasa arab ketika menyebutkan contoh-contoh penerapan maqashid as-syariah.
Pemahaman Hadis Barra‟ bin Azib yang terdapat di Sahih Bukhari misalnya. Dalam Hadis tersebut disebutkan jika Rasulullah Saw. melarang penggunaan bantalan berwarna merah, dan penyebutannya bersamaan dengan larangan penggunaan wadah perak dan pakaian sutra.
Alih-alih menggunakan pendekatan kebahasaan, Ibn Asyur justru menyinggung keadaan yang ada pada zaman Rasulullah Saw. terkait pakaian. Pada masa itu warna merah adalah warna yang aneh, penggunaanya dikhawatirkan akan menimbulkan rasa bangga berlebihan, sehingga Rasulullah Saw. memperingatkan para sahabat.
Pendekatan kontekstual ini lalu menjadi argumen dia bahwa larangan penggunaan bantalan merah di Hadis tersebut bukan haram melainkan makruh, meskipun disebutkan berurutan dengan hal-hal yang diharamkan dengan dalil nas lain dan teksnya berbunyi نهانا yang secara eksplisit menunjukkan pada larangan.
Metode Penetapan Maqashid As-Syariah
Cara untuk mengetahui dan menetapkan maqashid as-syariah dalam pandangan Ibn
Asyur ada tiga : Pertama, Riset terhadap konklusi hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat. Cara ini bisa ditempuh dengan mengkaji hukum-hukum yang sudah diketahui sebab penetapannya, lalu dipadukan menjadi satu baris yang kemudian melahirkan kesimpulan bahwa garis persamaan antara sebab hukum-hukum tersebut adalah maqashid as-syariah.
Semisal riset yang dilakukan Ibn Asyur pada keharaman jual beli borongan, membeli kurma basah dengan kurma kering dan perbuatan curang di dalam transaksi.
Sebab diharamkannya dua hal pertama adalah ketidaktahuan dua pihak yang bertransaksi terhadap kadar dari komoditas yang diperjualbelikan.
Sedangkan kasus ketiga haram karena adanya penipuan pada salah satu pihak. Dua sebab ini memiliki satu kesamaan, yaitu kerugian dan mudarat yang diderita oleh dua atau salah satu pihak yang bertransaksi.
Kesamaan ini adalah maqashid as-syariah dari tiga keputusan hukum tersebut, sehingga bisa disimpulkan semua transaksi yang menimbulkan kerugian pada dua belah pihak diharamkan.
Jalur lain yang bisa ditempuh adalah telaah hukum-hukum yang memiliki kesamaan sebab, yang melahirkan pemahaman bahwa sebab yang sama-sama dimiliki oleh masing- masing hukum tersebut adalah maqashid as-syariah di balik penetapannya.
Seperti hukum haram menjual sesuatu yang masih belum diserahterimakan, jual beli makanan dengan makanan secara tempo dan penimbunan.
Tiga hukum ini memiliki satu sebab yang sama yaitu menghambat ketersediaan barang di pasar, yang selanjutnya memberikan kesimpulan bahwa stabilitas pasokan komoditas pasar adalah maqashid as-syariah yang harus dijaga.
Metode riset ini tidak hanya berguna dalam memberi simpul pada kasus yang sudah ada putusan hukumnya, tetapi juga berfungsi pada peristiwa kekinian yang belum pernah disinggung dalam nas dalil hukum maupun pendapat ulama terdahulu.
Sistem transaksi modern yang juga menimbulkan kemudaratan bagi dua pihak yang terlibat, meskipun tidak ada pandangan ulama masa dulu juga dihukumi haram, karena maqashid as-syariah berlaku umum tidak parsial sebagaimana ‘illat dalam ushul fikih.
Kedua, Melalui teks dalil Alquran yang hampir tidak memiliki kemungkinan untuk ditujukan pada makna selain yang dikandung secara bahasa.
Status Alquran sebagai dalil yang qothiy secara transmisi ketika dipadukan dengan kekuatan indikasi teks akan melahirkan suatu maksud yang tidak perlu diperdebatkan lagi.
Maksud yang ditimbulkan oleh kombinasi sanad dan matan ini disebut dengan maqashid as-syariah, seperti makna ayat 185 Al-Baqarah dan ayat 78 surah Al-Hajj.
Kedua ayat ini secara gamblang menyebutkan bahwa Allah Swt. tidak menginginkan adanya kesulitan dalam beragama, maka kemudahan dalam menjalankan ajaran agama adalah maqashid as-syariah yang harus terpenuhi.
Ketiga, Hadis mutawatir baik secara maknawi maupun melalui perbuatan sahabat. Mutawatir maknawi semisal anjuran wakaf yang bisa dibuktikan dengan pengamalan istri-istri Rasulullah Saw., para sahabat dan tabiin di Madinah.
Pengamalan para sahabat membuktikan bahwa tujuan menebar kemanfaatan dan kemudahan bagi sesama lewat wakaf adalah maqashid as-syariah, karena pengamalan mereka menjadi indikasi akan keumuman cakupan anjuran wakaf, bukan hanya pada segelintir kalangan saja.
Mutawatir melalui perbuatan sahabat seperti Abu Barzah Al-Aslami yang membatalkan salat untuk mengejar kuda. Ketika diklarifikasi, Abu Barzah menjawab kalau dia pernah membersamai Rasulullah Saw. dan beliau tidak pernah menegurnya atas perbuatan tersebut.
Jawaban ini menunjukkan pada kemutawatiran perbuatan Rasulullah Saw. dalam memberikan keringanan beragama seperti yang disaksikan Abu Barzah, yang kemudian dia simpulkan sebagai maqashid as-syariah.
Ibn Bayyah menanggapi kedua metode ini dan melihatnya sebagai bentuk inkonsistensi Ibn Asyur. Jika cara mengetahui maqashid as-syariah adalah meninjau ketegasan teks dalil Alquran dan kepastian transmisi Hadis, maka ini berarti membutuhkan peran kajian kebahasaan dan tidak termasuk maqashid as-syariah seperti yang disebutkan di definisi. Dengan arti, unsur kebahasaan harus dilibatkan dalam proses penggalian maqashid as-syariah seperti paparan As-Syathibi.
Tanggapan Ibn Bayyah pada metode kedua mungkin tepat, karena memang secara samar-samar Ibn Asyur menerima adanya pengaruh aturan bahasa arab di metode ini, dan hal tersebut bertentangan tidak hanya dengan definisi tetapi juga motivasi awal gagasan ilmu maqashid as-syariah.
Namun untuk metode Hadis mutawatir secara maknawi tidak ada kontradiksi dengan definisi dan spirit Ibn Asyur, karena pengambilan maqashid as-syariah di metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan unsur kebahasaan.
Justru kaidah logika yang lebih kentara pengaruhnya di sini, sebab secara mantik sesuatu yang dinukil mutawatir harus diterima sebagaimana penerimaan hasil panca indera.
Berbeda dengan jenis mutawatir yang kedua pada contoh Abu Barzah Al-Aslami. Memang status perbuatan Rasulullah Saw. dan maqashid as-syariah yang disarikan darinya jika dinisbatkan pada Abu Barzah adalah hampir qothiy, namun tidak demikian bagi sahabat dan tabi‟in yang mendengarkan. Lalu apa faedah penyebutan metode ini ? Bukankah ini berlawanan dengan apa yang digaungkan Ibn Asyur tentang kepastian kaidah pemahaman nas dalil ?.
Terlepas dari beberapa kejanggalan dalam tawaran metode penetapan maqashid as- syariah di atas, terlihat bagaimana upaya Ibn Asyur untuk merumuskan kaidah-kaidah yang sesuai dengan format ideal dia: menjadi standar penengah perbedaan pendapat.
Rumusan tiga metode ini mempunyai nuansa penerapan prinsip-prinsip logika yang kuat. Metode pertama sama dengan konsep induksi dalam ilmu mantik, karena berupa analisis hal-hal parsial untuk menemukan kesimpulan universal.
Sedangkan metode ketiga adalah dalil burhan dalam istilah mantik yang harus diamini kebenarannya. Adapun metode kedua, maka ini termasuk serapan dari ilmu ushul fikih yang Ibn Asyur ambil sebab kekuatan indikasinya.
Fitrah sebagai Tolok Ukur
Nilai-nilai yang dibawa Islam selaras dengan ruh kemanusiaan, karena dibangun di atas prinsip fitrah yang pasti dimiliki setiap orang.
Fitrah dengan pengertian “keadaan awal akal manusia yang Allah Swt. ciptakan, bebas dari pemahaman yang salah dan kebiasaan buruk” merupakan akal budi murni yang harus dijaga eksistensinya supaya manusia tidak kehilangan substansi.
Tidak heran bila fitrah adalah maqashid as-syariah terbesar yang Allah Swt. jadikan sebagai sifat dari agama Islam seperti pada ayat 30 surah Ar-Rum.
Berpijak pada urgensitas fitrah ini, Ibn Asyur menawarkan metode penetapan hukum yang bertolak dari maqashid as-syariah fitrah.
Segala perbuatan yang menyebabkan hilangnya fitrah manusia maka diharamkan, dan perbuatan yang berfungsi menjaga dan melestarikan fitrah hukumnya wajib secara syariat.
Misal hak hidup adalah fitrah manusia, maka perbuatan- perbuatan yang bisa menghilangkan hak ini seperti membunuh mempunyai konskuensi hukum haram, dan tindakan membela diri ketika terancam adalah wajib karena untuk menjaga fitrah hak hidup tadi.
Adapun tingkah laku yang tidak sampai menghilangkan, hanya sekedar mengganggu stabilitas fitrah, maka hukumnya juga haram namun dengan skala larangan yang lebih minimal.
Begitu juga kaitannya dengan perbuatan yang membantu mestabilkan fitrah, memiliki hukum wajib. Seperti berlaku jujur dan amanah dalam kegiatan transaksional berpijak pada fitrah keinginan manusia untuk hidup dengan damai tanpa adanya perselisihan.
Tindakan jujur ini dianjurkan karena mendukung stabilitas hidup damai, dan perbuatan curang juga menipu haram karena mengganggu kondisi keinginan fitrah tersebut.
Sedangkan hal-hal di luar dua ciri menghilangkan dan mengganggu di atas hukumnya mubah.
Pembagian skala maksimal-minimal tingkatan haram-wajib ini penting disebutkan karena menjadi standar ketika terjadi pertentangan dua fitrah, yang didahulukan kemudian fitrah yang memiliki ukuran prioritas lebih tinggi.19 Seperti eksperimen medis beresiko menggunakan manusia dan hewan.
Fitrah manusia adalah hak hidup tanpa adanya gangguan untuk alasan apapun, dan fitrah hewan ialah dimanfaatkan manusia sebagai makanan dan peliharaan.
Pemanfaatan manusia untuk menjadi kelinci percobaan bertentangan dengan fitrah asalnya, berbeda dengan hewan yang memang untuk dimanfaatkan, hanya saja penggunaannya tidak sesuai yaitu bukan dimakan dan dipelihara. Maka dalam kasus ini, larangan penggunaan manusia lebih diprioritaskan daripada hewan.
Klasifikasi Hadis Rasulullah Saw.
Sebagian besar ketentuan hukum Islam diambil dari Hadis Rasulullah Saw. lebih-lebih dalam urusan muamalah, maka penyusunan metode memahami Hadis menjadi penting. Ibn
Asyur mengajukan metode klasifikasi Hadis Rasulullah Saw., sebagai ganti dari pendekatan kebahasaan ilmu ushul fikih dan jawaban atas keraguan sebagian ulama dalam menentukan sikap terkait perbuatan Rasulullah Saw., apakah termasuk kebiasaan yang tidak ada hubungannya dengan hukum Islam atau tidak.
Dalam klasifikasi Hadis versi Ibn Asyur, perbuatan dan perkataan yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. bisa dibagi menjadi dua belas kondisi : pensyariatan, fatwa, penyelesaian sengketa sebagai hakim, pengambilan kebijakan selaku pimpinan negara, bimbingan, solusi bagi dua pihak yang bertengkar, petunjuk, nasehat, penyempurnaan diri, tuntunan pada nilai- nilai luhur, didikan dan kegiatan sehari-hari.
Hadis yang diriwayatkan dengan tiga kondisi pertama, hukum yang dikandung antara wajib jika berupa perintah dan haram jika berbentuk larangan. Delapan situasi selanjutnya menunjukkan antara hukum sunah dan makruh, sedangkan yang terakhir tidak terikat dengan hukum tertentu.
Ciri dari Hadis yang diriwayatkan dengan tiga situasi pertama adalah adanya indikasi keinginan Rasulullah Saw. agar sabda beliau di sampaikan ke khalayak umum, juga semangat beliau untuk melakukannya, serta Hadis tersebut berbentuk kaidah umum.
Ciri semacam ini bisa ditemukan dalam Hadis tentang hukum wasiat pada ahli waris dan perintah Rasulullah Saw. kepada para sahabat untuk meniru ritual haji beliau.
Adapun petunjuk yang membedakan delapan kondisi yang lain adalah tidak adanya tekanan dari Rasulullah Saw. dalam pelaksanaan perintah ataupun larangan beliau.
Seperti Hadis Nu‟man bin Basyir ketika sang ayah Basyir bin Sa‟ad memberi hadiah kepadanya namun tidak pada saudaranya yang lain.
Rasulullah Saw. kemudian melarang Basyir melakukan hal demikian sembari menimpali: “Tidak, mintalah orang selainku untuk menjadi saksi.”
Seandainya larangan beliau pada posisi sebagai pemangku kebijakan syariat, maka tidak mungkin Basyir diberi kelonggaran untuk mencari orang lain menjadi saksi.
Pendekatan klasifikasi Hadis Ibn Asyur ini begitu berbeda dengan pola ilmu ushul fikih klasik yang menitik beratkan pada aspek kebahasaan.
Adanya teks amr dengan indikasi asal pada hukum wajib dan nahi yang menunjukkan pada haram lalu menjadi tidak perlu diperhatikan.
Pemilahan kondisi Rasulullah Saw. ketika bersabda dan bagaimana kondisi sosial pada saat itu balik menjadi pisau analisis utama.
Epilog
Kritik terhadap suatu bangunan keilmuan adalah sesuatu yang lazim, karena kritik adalah bukti sahih adanya pembacaan secara menyeluruh terhadap ilmu tersebut. Hal ini juga menjadi bukti bahwa tidak ada yang statis, semua pasti berkembang secara dinamis sesuai
dengan perkembangan waktu. Ilmu ushul fikih dengan segala kerapihan konsepnya pada masa sekarang mungkin relevan dalam mencari argumentasi dalam forum diskusi dan memperkuat dalil putusan hukum suatu madzhab, tetapi dua hal ini tidak cukup bagi seorang Thahir bin Asyur, perlu fungsi yang lebih radikal lagi sehingga dia menawarkan alternatif metodologi baru.
Sebaliknya, tawaran Ibn Asyur bukanlah hal yang sempurna betul, setelah ditelaah lagi masih ada lobang di sana-sini yang perlu ditambal.
Dialektika yang terjadi di antara dua kutub metodologi klasik dan kontemporer ini bukan suatu bentuk kekacauan metodologis, justru merupakan sebuah keberkahan yang perlu disyukuri, karena pada akhirnya akan mengantarkan pada kematangan metodologis penetapan hukum Islam sehingga bisa berdiri sejajar dengan metode hukum-hukum modern dan beriringan dengan laju perkembangan zaman.
Oleh: Muhammad Asrori AS