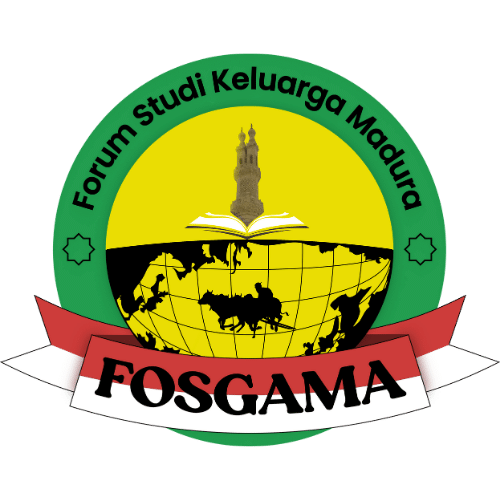FOSGAMA Mesir – Derasnya arus informasi dan dahsyatnya perkembangan teknologi di era modern saat ini telah menciptakan sebuah arus baru yang saya sebut sebagai “kekeringan spiritualitas”.
Kehadiran media sosial dengan segala informasi yang dimuatnya sedikit banyak telah menyita waktu dan mendistraksi kehidupan masyarakat modern.
Hal seperti ini kemudian menuntut adanya kebutuhan mereka terhadap kesejukan hati dan kedamaian jiwa dalam menjalani kehidupan.
Dalam arti bahwa, mereka pada hakikatnya membutuhkan spiritualitas di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin maju.
William James, seorang psikolog terkemuka abad ke-20, sebagaimana yang disampaikan oleh Haidar Bagir, mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan menemukan kepuasan kecuali jika ia bersahabat dengan Kawan Yang Agung (The Great Socius).
Tentu, kata Haidar Bagir, Kawan Agung yang dimaksud adalah Tuhan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa selama manusia itu belum berkawan dengan Kawan Yang Agung itu, maka selama itu pula ia akan merasakan adanya kekosongan dalam hidupnya.
Dalam menghadapi situasi kehidupan yang demikian, tasawuf menjadi sebuah oase yang bisa menyelamatkan kekeringan spiritualitas masyarakat modern.
Tersebab, tasawuf selain sebagai ajaran Islam yang membincang seputar laku spiritual, ia juga bisa disebut sebagai laku spiritual itu sendiri.
Namun, tasawuf seperti apa yang seharusnya dikembangkan? Apakah tasawuf yang hanya menekankan kepada sebuah laku yang harus meninggalkan kenikmatan dunia dan menjauhi kehidupan sosial masyarakat?
Secara sepintas, dunia sufistik terdengar menakutkan dan mengerikan bagi masyarakat modern. Ia dipahami sebagai sebuah laku yang menjadikan orang yang menempuhnya
harus rela meninggalkan aktivitas sosial, menjauhi kehidupan publik, membenci harta dan segala hal yang bersifat duniawi.
Semua itu dilakukan dalam rangka agar pelaku tasawuf fokus dalam melakukan olah jiwa (riyadhat an-nafs) dan pembersihan jiwa (tazkiyat an-nafs) sehingga tidak ada lagi ikatan kecuali antara dirinya dengan Tuhannya semata.
Dalam sejarahnya, Istilah “tasawuf” baru muncul pada paruh pertama abad ke-3 H. Sebelumnya, yakni mulai akhir abad ke-1 H sampai kurang lebih abad ke-2 H, laku spiritual disebut sebagai zuhud (asketisme) dan orang yang menjalaninya disebut sebagai zahid.
Pada perkembangannya, zuhud kemudian menjadi bagian dari salah satu ajaran penting dalam tasawuf dan menjadi salah satu tangga yang harus dilalui oleh orang yang menempuh jalan tasawuf. Bahkan bisa dikata, tidak sempurna kesufian seseorang tanpa melakukan zuhud.
Secara etimologis, zuhud berasal dari akar kata za-ha-da yang memiliki arti menahan diri dari sesuatu yang disenangi atau meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh dilakukan.
Sedangkan ditinjau dari terminologisnya, al-Ghazali di dalam masterpiece-nya, Ihya Ulumiddin, mendefinisikan zuhud sebagai sebuah ungkapan dari ketidaksenangan seorang hamba terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dengan cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang yang bersifat ukhrawi.
Dengan bahasa yang lain, zuhud adalah memutus hubungan dengan sesuatu selain Allah dan fokus menjalin hubungan dengan-Nya.
Lebih jauh lagi, al-Ghazali menganjurkan para penempuh jalan tasawuf untuk melakukan zuhud. Sebab dalam pandangannya, zuhud diperhitungkan sebagai maqam mulia yang dilalui oleh seorang salik (sebutan bagi orang yang menempuh jalan tasawuf).
Anjuran melakukan zuhud dalam bertasawuf pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh keyakinan kalangan sufi bahwa manusia cenderung terlalu menikmati hal-hal duniawi yang disenangi sehingga ia akan terjerambab dalam sikap yang terlalu berlebihan.
Untuk mencapai maqam zuhud ini, para sufi kemudian melakukan sebuah kontemplasi agar mereka bisa fokus bercengkrama dengan Tuhannya tanpa ada gangguan dari godaan dunia.
Saya kira menarik, dalam hal ini, menyampaikan gagasan Ibnu Bajah sebagaimana yang dituliskan Muhammad Yusuf asy-Syaikh dalam bukunya, Maqalat fi al-‘Aqidah wa al-Mantiq wa at-Tasawwuf. Menurutnya, menjauhi kehidupan publik yang dianjurkan
kalangan sufi bukan berarti memutus hubungan dengan sosial masyarakat. Akan tetapi anjuran tersebut dimaksudkan agar seorang salik bisa mengontrol diri dan menguasai syahwatnya sehingga tidak tenggelam dalam keburukan-keburukan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Artinya seorang salik tetap bisa bergaul di tengah kehidupan sosial dengan tetap mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus dalam kehinaannya.
Pandangan Ibnu Bajah di tengah krisis spiritulitas yang menjangkit masyarakat modern saat ini penting untuk digelorakan kembali.
Laku sufisme seyogyanya tidak dipahami sebagai sesuatu angker dan menakutkan yang hanya bisa ditempuh oleh orang-orang tertentu.
Akan tetapi, nilai-nilai sufisme ini bisa masuk dalam segala relung kehidupan masyarakat modern. Kita hanya perlu mengubah sudut pandang kita terhadap gaya hidup yang kita jalani.
Cara pandang sufisme terhadap hal-hal duniawi tidak berarti harus meninggalkan dunia seutuhnya. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita tidak menghamba kepada dunia sehingga dunia tidak hanya menjadi pemuas nafsu saja.
Dunia seharusnya dikelola dengan baik, sebab pada sejatinya, dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat.
Hal tersebut menunjukkan bahwa hal-hal duniawi menjadi penting dalam mengelola perjalanan hidup kita saat ini untuk menggapai tujuan utama kita, yaitu kebahagian di akhirat kelak.
Yang buruk adalah jika kita terlalu berambisi dengan dunia sehingga pada akhirnya kita lalai dalam mengendalikan hawa nafsu kita.
Begitu pula, cara pandang yang demikian bisa diaplikasikan dalam ranah bermedia sosial (semisal) sebagai salah satu sisi kehidupan masyarakat modern.
Cara pandang sufisme terhadap aktivitas media sosial bukan berarti meninggalkan media sosial sepenuhnya.
Sebab media sosial juga memberikan beberapa informasi penting dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri agar tidak tenggelam dalam kemudahan media sosial tanpa menyaring informasi yang begitu banyaknya.
Apalagi sampai hanyut dalam euforia media sosial yang kemudian banyak menyita waktu kita yang berharga.
Sejatinya, prinsip yang ingin saya tegaskan di sini adalah apa yang dianggap buruk dalam euforia dunia ini bukan terletak pada eksistensi–dzatiah–nya, akan tetapi terletak pada
tatanan aplikatifnya dalam mengelola dunia. Maka dari itu, spirit sufistik yang demikian menjadi penting dan menemukan relevansinya dalam menghadapi situasi kekeringan spiritulitas masyarakat modern tanpa ada bayang-bayang ketakutan untuk bertasawuf.
Nilai-nilai sufistik semacam ini patut dikembangan di era modern saat ini dalam rangka memberikan alternatif cara hidup ruhani yang mengarah pada terbentuknya sebuah tatanan spiritualisme peradaban masyarakat madani, bukan spiritualisme yang dekaden.
Oleh: Hamim Maftuh Elmy